Sunyi dalam Seragam, Ketika Bhabinkamtibmas Gantung Diri dan Tak Ada yang Mendengar
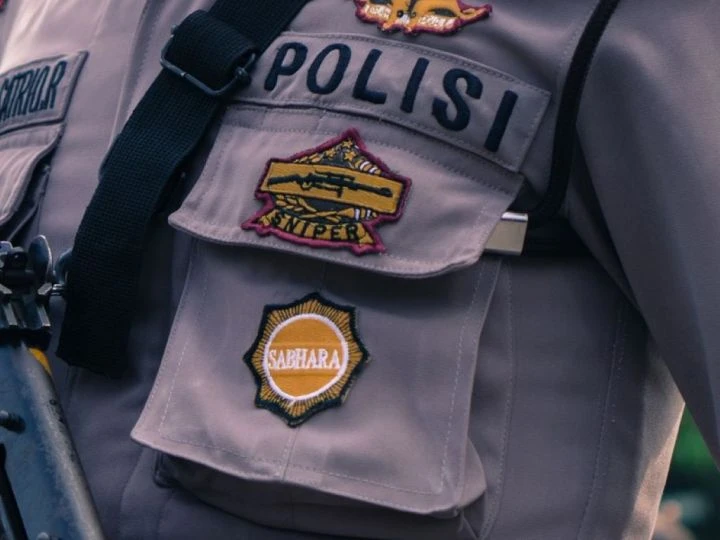
bbn/medcom/ilustrasi/Sunyi dalam Seragam, Ketika Bhabinkamtibmas Gantung Diri dan Tak Ada yang Mendengar.
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Kabar duka kembali menyelimuti Bali. Seorang anggota kepolisian, Aiptu Made Suwenten, yang selama ini mengemban tugas sebagai Bhabinkamtibmas Polsek Sukasada, ditemukan meninggal dunia dengan cara tragis, gantung diri di kandang sapinya sendiri.
Peristiwa ini tidak hanya mengejutkan masyarakat Desa Sambangan, tapi juga mengguncang kesadaran kita bersama tentang kondisi kesehatan jiwa para apparat keamanan yang selama ini menjadi ujung tombak keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sebagai petugas yang dikenal dekat dengan warga, Bhabinkamtibmas memiliki beban tugas sosial yang tidak ringan. Mereka bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi juga figur pembina, pelindung, dan penyambung aspirasi warga. Ketika sosok seperti ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, kita wajib bertanya lebih dalam: Apa yang luput kita lihat?
Perspektif Psikiatri: Stigma, Tekanan Emosional dalam Profesi yang Sunyi
Dalam perspektif psikiatri, bunuh diri adalah fenomena multifaktorial dan merupakan hasil akhir dari penderitaan mental yang berkepanjangan. Terdapat kombinasi kompleks antara faktor biologis (seperti gangguan depresi mayor, bipolar, atau PTSD), psikologis (kesepian, kelelahan emosional), dan sosial (stigma, tekanan pekerjaan, konflik personal).
Dalam kasus Aiptu Made Suwenten, belum ada informasi lengkap terkait latar belakang medis atau psikososialnya. Namun, pola ini sering kali serupa: individu yang mengalami tekanan berat tidak mendapatkan ruang yang aman untuk mengekspresikan beban emosionalnya.
Di institusi seperti kepolisian, keberanian dianggap sebagai atribut utama. Namun sering kali keberanian ini disalahartikan sebagai ketabahan absolut tanpa celah untuk merasa lelah, rapuh, apalagi meminta pertolongan. Ada budaya diam yang mengakar kuat bahwa mengakui kelelahan mental dianggap sebagai kelemahan.
Salah satu masalah utama adalah stigma internal dalam institusi. Polisi sering kali dianggap harus kuat secara mental, tidak boleh menunjukkan kelemahan, apalagi mengeluh. Akibatnya, banyak yang menyimpan beban dalam diam, dan menolak atau tidak tahu ke mana harus mencari pertolongan.
Budaya maskulinitas yang kaku dalam institusi kepolisian membuat ekspresi emosi dan kerentanan dianggap tabu. Dalam jangka panjang, kondisi ini menjadi "bom waktu" psikologis yang bisa meledak dalam bentuk agresi, disfungsi keluarga, atau bahkan keputusasaan ekstrem. Ini menjadi ironi tragis dimana para petugas yang menjaga keamanan publik justru tidak memiliki cukup akses terhadap perlindungan psikologis bagi diri mereka sendiri.
Data global mencatat bahwa petugas kepolisian memiliki tingkat bunuh diri 54% lebih tinggi dibandingkan populasi umum. Di Amerika Serikat, pada 2019 tercatat bahwa lebih banyak polisi meninggal karena bunuh diri dibandingkan karena tugas operasional. Angka yang mirip juga dilaporkan di Prancis dan Kanada, yang menunjukkan bahwa beban kerja, paparan kekerasan, serta kultur organisasi yang minim dukungan emosional meningkatkan kerentanan psikis personel kepolisian.
Sayangnya, di Indonesia data ini belum banyak dipublikasikan, namun laporan investigatif dari berbagai media menunjukkan pola yang serupa—tingginya angka stres, depresi, hingga ide bunuh diri pada kalangan aparat, terutama di daerah terpencil atau dengan intensitas kerja tinggi.
Perlunya Dukungan Psikososial yang Terintegrasi
Kejadian ini harus menjadi pemantik untuk meninjau kembali sistem pendampingan psikologis bagi para petugas lapangan. Apakah sudah tersedia layanan konseling yang bisa diakses tanpa stigma? Apakah ada pelatihan penguatan mental yang tidak semata formalitas? Apakah lingkungan kerja memberikan ruang bagi personel untuk berbicara secara jujur tentang kelelahan atau tekanan pribadi?
Intervensi yang dibutuhkan bukan hanya berbentuk pelatihan mental health awareness, tetapi juga mekanisme praktis yang terintegrasi dalam struktur organisasi. Misalnya, sistem skrining psikologis rutin layaknya medical checkup yang selama ini ditujukan hanya untuk melihat kondisi fisik saja, pembentukan peer support group, hingga pelibatan psikiater dan psikolog dalam mendampingi anggota kepolisian di daerah rawan tekanan kerja tinggi.
Suara Jiwa Kita Semua
Kasus ini bukan sekadar catatan tragis, melainkan juga panggilan moral untuk kita semua. Kita tidak bisa lagi menunggu tragedi demi tragedi untuk mulai mengakui pentingnya kesehatan jiwa. Kita perlu membangun sistem yang lebih manusiawi, yang menghargai perasaan sebagai bagian tak terpisahkan dari tugas dan pengabdian.
Perlu ada keberanian untuk membangun sistem yang lebih manusiawi, lebih terbuka, dan lebih peduli. Menjaga aparat dari luka yang tak terlihat adalah bentuk penghormatan kita atas pengabdian mereka. Dan mungkin, dengan langkah kecil seperti menyediakan ruang bicara dan mendengarkan keluh kesah mereka, kita sedang menyelamatkan satu jiwa yang berharga.
Mari kita rawat para penjaga ketertiban itu bukan hanya sebagai aparatur, tapi sebagai manusia. Yang kadang juga merasa lelah, bingung, dan butuh didengarkan. Mari kita jadikan Suara Jiwa ini sebagai panggilan untuk menghapus sunyi dari profesi yang selama ini terlalu sering memendam luka dalam diam. Karena menjaga jiwa, baik milik sendiri maupun orang lain, adalah tanggung jawab kita bersama. (Prof Dr dr Cokorda Bagus Jaya Lesmana, SpKJ(K), MARS)
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/tim